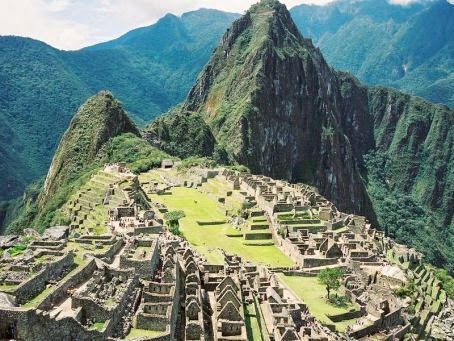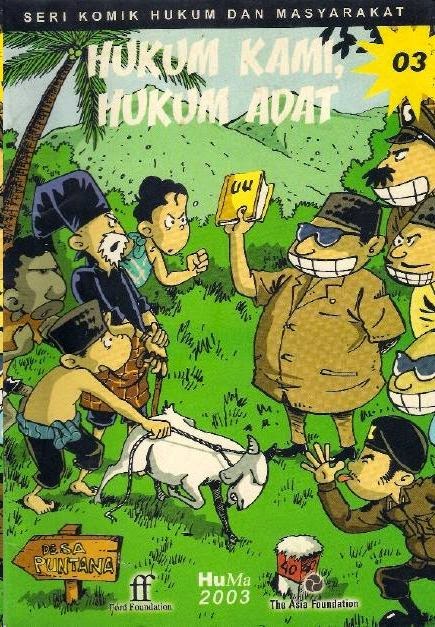Literasi yang dalam bahasa inggrisnya literacy berasal dari bahasa Latin yaitu litera (huruf) sering diartikan sebagai keaksaraan. Jika dilihat dari makna hurufiah literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Seringkali orang yang bisa membaca dan menulis disebut literat, sedangkan orang yang tidak bisa membaca dan menulis disebut iliterat atau buta aksara.
Kern (2000: 3) menjelaskan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Selain itu literasi juga memiliki kesamaan arti dengan belajar dan memahami sumber bacaan.
Romdhoni (2013: 90) menyatakan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan-keterampilan tertentu, yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Kern (2000: 16) yang mendefinisikan :
“literasi secara lebih komprehensif sebagai berikut: Literacy is the use of socially, historically, and culturally-situased practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationship beetween textual conventions and their contexts of use and, ideally, the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic-not static-and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written an spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge. (Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, dan situasi kebudayaan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antar konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis-tidak statis- dan dapat bervariasi diantara dan didalam komunitas dan kebudayaan. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kebudayaan).”
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas pada dasarnya dapat dijelaskan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang dilengkapi keterampilan-keterampilan untuk menciptakan dan menginterprestasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan.
Lalu senada dengan itu Iriantara (2009: 5) menjelaskan bahwa kini literasi bukan hanya berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis teks saja, karena kini “teks” sudah diperluas maknanya sehingga mencakup juga “teks” dalam bentuk visual, audiovisual dan dimensi-dimensi kompiterisasi, sehingga di dalam “teks” tersebut secara bersama-sama muncul unsur-unsur kognitif, afektif, dan intuitif.
Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan inrormasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejehteraan hidup (peradaban unggul).
 |
| Gambar: Pengertian Literasi |
Jenis-Jenis literasi
Menurut Ibnu Adji Setyawan (2018: 1) istilah literasi sudah mulai digunakan dalam skala yang lebih luas tetapi tetap merujuk pada kemampuan atau kompetensi dasar literasi yakni kemampuan membaca serta menulis. Intinya, hal yang paling penting dari istilah literasi adalah bebas buta aksara supaya bisa memahami semua konsep secara fungsional, sedangkan cara untuk mendapatkan kemampuan literasi ini adalah dengan melalui pendidikan. Sejauh ini, terdapat 9 macam literasi, antara lain:
- Literasi Kesehatan merupakan kemampuan untuk memperoleh, mengolah serta memahami informasi dasar mengenai kesehatan serta layanan-layanan apa saja yang diperlukan di dalam membuat keputusan kesehatan yang tepat.
- Literasi Finansial yakni kemampuan di dalam membuat penilaian terhadap informasi serta keputusan yang efektif pada penggunaan dan juga pengelolaan uang, dimana kemampuan yang dimaksud mencakup berbagai hal yang ada kaitannya dengan bidang keuangan.
- Literasi Digital merupakan kemampuan dasar secara teknis untuk menjalankan komputer serta internet, yang ditambah dengan memahami serta mampu berpikir kritis dan juga melakukan evaluasi pada media digital dan bisa merancang konten komunikasi.
- Literasi Data merupakan kemampuan untuk mendapatkan informasi dari data, lebih tepatnya kemampuan untuk memahami kompleksitas analisis data.
- Literasi Kritikal merupakan suatu pendekatan instruksional yang menganjurkan untuk adopsi perspektif secara kritis terhadap teks, atau dengan kata lain, jenis literasi yang satu ini bisa kita pahami sebagai kemampuan untuk mendorong para pembaca supaya bisa aktif menganalisis teks dan juga mengungkapkan pesan yang menjadi dasar argumentasi teks.
- Literasi Visual adalah kemampuan untuk menafsirkan, menciptakan dan menegosiasikan makna dari informasi yang berbentuk gambar visual. Literasi visual bisa juga kita artikan sebagai kemampuan dasar di dalam menginterpretasikan teks yang tertulis menjadi interpretasi dengan produk desain visual seperti video atau gambar.
- Literasi Teknologi adalah kemampuan seseorang untuk bekerja secara independen maupun bekerjasama dengan orang lain secara efektif, penuh tanggung jaab dan tepat dengan menggunakan instrumen teknologi untuk mendapat, mengelola, kemudian mengintegrasikan, mengevaluasi, membuat serta mengkomunikasikan informasi.
- Literasi Statistik adalah kemampuan untuk memahami statistik. Pemahaman mengenai ini memang diperlukan oleh masyarakat supaya bisa memahami materi-materi yang dipublikasikan oleh media.
- Literasi Informasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di dalam mengenali kapankah suatu informasi diperlukan dan kemampuan untuk menemukan serta mengevaluasi, kemudian menggunakannya secara efektif dan mampu mengkomunikasikan informasi yang dimaksud dalam berbagai format yang jelas dan mudah dipahami.
Sumber: Dikutip dari berbagai sumber
Sekian uraian tentang Pengertian Literasi Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.